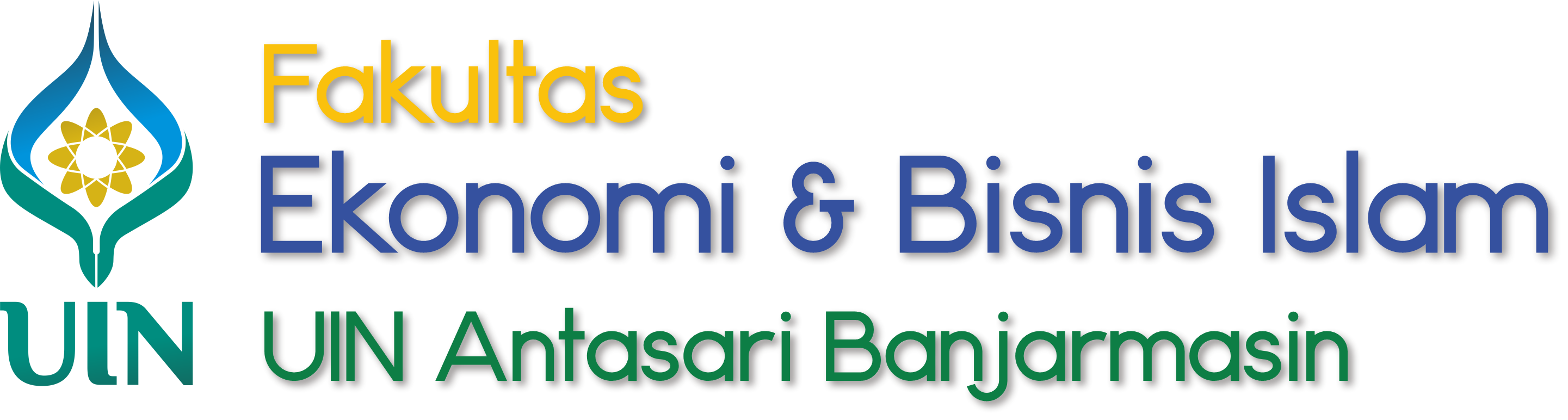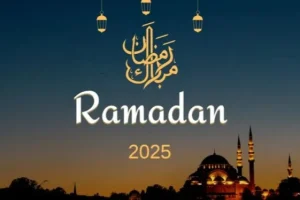Mazhab Fikih
Oleh: Dr. H. Sukarni, M.Ag
Sambil iseng dengan mahasiswa baru, saya bertanya. Apa bedanya antara sekolah dan kuliah. Bermacam-macam jawabannya dari yang serius hingga yang goyon. Salah seorang mahasiswi sambil tersenyum menjawab, menemukan jodoh pak. Saya tersenyum, karena ternyata saya menemukan jodoh juga saat kuliah. Betul juga saya pikir jawaban mereka. Namun saya agak serius menjelaskan kepada mereka yang baru masuk kuliah pertama dengan saya. Saya katakan coba anda periksa, kata “kuliah” itu berasal dari bahasa apa. Seperti kebiasaan generasi Z, dengan gerakan cepat jemari, mereka menemukan jawabannya, bahasa Arab Pak, “kulliyyat” artinya keseluruhan. Nah, saya bilang, berarti kalau kita kuliah, kita akan menemukan “keseluruhan”, keseluruhan ilmu seluas pengetahuan yang dimiliki dosen atau seluas kemampuan kita untuk menemukan pengetahuan yang diajarkan dosen, baik melalui pembelajaran kelas atau pembelajaran mandiri, bahkan melalui riset mandiri atau kolaborasi. Sebagian mereka manggut-manggut. Lalu dengan pelan saya jelaskan, bahwa termasuk materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini tentang fikih.
Hal paling awal yang saya perkenalkan adalah tentang perbedaan antara agama (din), ajaran (syariah), dan hukum (fiqh) dengan ilustrasi piramida terbalik. Tiga term tersebut menjadi kunci untuk mehamai fikih secara kulliyyat. Fikih adalah hasil ijtihad, hasil berpikir untuk menentukan hukum. Pada mulanya sederhana, ijtihad hanyalah menentukan muatan amar atau nahi dalam sebuah teks dalil. Kalau muatan amarnya keras maka hasilnya wajib, kalau sekedar amar anjuran hukumnya sunnat saja. Juga kalau nahinya tegas berarti haram, kalau hanya anjuran menghindari, maka hukumnya makruh. Kalau netral berarti mubah. Itulah pendekatan kebahasaan dalam berijtihad untuk menentukan hukum yang ada teks dalilnya.
Persoalan mulai rumit saat dalil secara teks tidak tersedia bagi suatu masalah. Dalam hal ini ulama melakukan upaya ekstraksi terhadap teks dalil yang menghasilkan konsep maqashid syariah yang intinya adalah bahwa syariah diberikan Tuhan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi lima hal : agama, jiwa, akal, keturunan, dan kepemilikan. Dengan berpikir maqashid, dirumuskan formula umum ijtihad, bahwa setiap hal yang berfungsi menentukan eksistensi lima hal tersebut hukumnya wajib; membantu eksistensi lima hal hukumnya mustahab; menyebabkan hilangnya eksistensi lima hal hukumnya haram; membantu menghilangkan eksistensi lima hal hukumnya makruh; tidak berpengaruh pada eksistensi lima hal hukumnya mubah. Begitulah seterusnya.
Mungkin relatif sama antar sesama alumni pondok pesantren tradisonal yang kemudian masuk kuliah di PTKIN, kalaulah tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam, cara berpikir menghadapi perbedaan mazhab pasti menggunakan model kacamata kuda, lurus ke depan dan cenderung mengabaikan (bahkan bisa menyalahkan) setiap pendapat yang berbeda dari pengetahuannya. Seperti yang diuraikan dalam hasil penelitian Martin van Bruinessen dalam “Kitab Kuning’nya, pondok Pesantren tradisional di Indonesia pada umumnya mengajarkan fikih mazhab Syafi’i, mulai dari kitab Syarah Sittiin (Sittiin Masalah) karya Syaikh Abu al Abbas Ahmad bin Hamzah bin Ahamd al Anshori al Romli (ulama Mesir, w. 1004), kitab Bajuri Ibnu Qasim karya Syaikh Ibrahim al-Bajuuri ibni Qasim (ulama Mesir, w. 1276), kemudian kitab I’anat ath-Thalibin Syarah Fathul Mu’in karya Abu Bakar ‘Utsman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi al-Bakri (ulama Mekkah, w. 1310), dan seterusnya. Sedikit sekali mengkaji ushul fikih, hanya kitab Al-Waraqaat fii Ushul al-Fiqh karya Al-Juwaini (ulama Iran, w. 478 H).
Pengalaman saya dalam pembelajaran fikih di pondok pesantren tradisional lebih diutamakan pada analisis bahasa, artinya kitab fikih tersebut lebih diposisikan sebagai media mempraktekkah hukum-hukum dalam struktur bahasa Arab yang dipelajari sebelumnya pada kitab nahwu dan sharaf. Namun, setelah kuliah di Fakultas Syariah IAIN Antasari (sekarang UIN), saya baru berkenalan dengan berbagai mazhab dalam fikih, juga dengan berbagai aliran dalam ushul fikih. Saya dan kita semua bersyukur memiliki guru (dosen) dalam berbagai aliran mazhab. Dengan demikian, semakin kaya perspektif keagamaan kita, terutama dalam bidang fikih.
Pada tingkat awam, sering terjadi kesalahan dalam memahami konsep mazhab, termasuk dalam disiplin teologi dan sufisme. Kekeliruan itu menumbuhkan fanatisme bermazhab yang cenderung terjerumus pada sikap klaim kebenaran (trurt claim). Pusaran klaim ini menjadi lahan subur munculnya sikap intoleran dalam paham beragama. Pada tingkat kritis, sikap intoleran ini dapat menjadi biang perpecahan atas nama mazhab, organisasi, afiliasi partai, dan simbol-simbol primordial lainnya.
Mazhab adalah pendapat seseorang atas dasar kompetensinya atau interpretasi seseorang terhadap nash dengan dasar logika akademik yang dimilikinya. Dengan demikian, mazhab tidaklah final, ia hanya kebenaran sepanjang (atau sependek) pengembaraan intelektual seseorang dalam mengejar menemukan kebenaran. Oleh karena itu, mazhab terkait erat dengan riwayat pendidikan, tempat tinggal/pergaulan intelektual, bahkan geneologi.
“Syukurlah kalian sudah masuk kuliah”, sapa saya kepada semua mahasiwa baru saat kuliah pertama unutk subjek fikih. “Kita akan membahas fikih dalam empat perspektif, sebagai ilmu (di samping keyakinan), sebagai pengetahuan yang tumbuh dalam sejarah (historis), sebagai mazhab (perbandingan pendapat), dan sebagai jawaban dari dinamika kehidupan (kontemporer)”, pungkas saya.