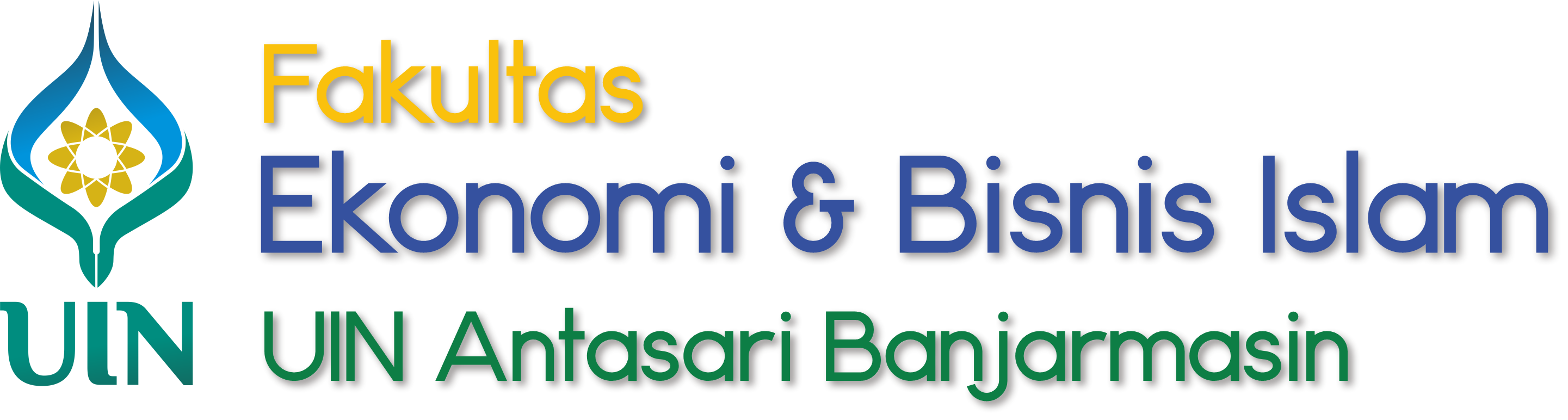Inflasi dan Kebijakan Pro Petani
Oleh: Muhammad Hikam, Lc., MA. Ek.
Beberapa waktu yang lalu, saya membeli beras di penjual langganan. Ia mengeluh harga beras di tingkat distributor sudah tinggi. Meskipun dengan untung yang tak banyak, ia tidak memiliki pilihan kecuali menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan masygul, ia menyebut angka-angka. Saya tidak tahu seberapa akurat angka itu. Tetapi saya bisa menangkap kegalauannya.
Tentu penjual beras itu tidak sendiri. Masyarakat kita juga merasakan harga beras yang cukup tinggi. Pemerintah turut berupaya keras untuk mengendalikan harga.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa harga beras adalah komponen inflasi terbesar di negeri kita, termasuk di Kalimantan Selatan. Bahkan, dalam batas tertentu, (isu) inflasi yang tidak terkendali dapat berakibat pada terjadinya ketidakstabilan politik dan sosial. Tak heran, harga beras menjadi menjadi perhatian pemerintah.
Namun patut disadari, secara mendasar, margin keuntungan dari harga gabah petani dari sawah menjadi penumpu peredaran uang di masyarakat petani desa. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi dari sisi permintaan, perlu dipastikan adanya pasokan yang melimpah dan kompetitif. Maksudnya, harga antar produsen dapat bersaing di sisi efisiensi biaya yang dilakukan produsen.
Inilah mengapa, meskipun mengalami panen raya, sebagian besar petani kita menjerit. Pasalnya, mereka dibiarkan “tarung bebas” melawan beras impor. Kebijakan praktis dan terkesan potong kompas ini menambah beban petani yang masih sulit mencari pupuk dan (kalaupun ada) harganya mahal. Dapat dibayangkan kondisi jika mereka mengalami gagal panen?
Padahal dalam konstruk politik ekonomi yang dianut bangsa kita, dikenal subsidi di sisi input, yaitu pupuk dan ada penugasan model korporasi BUMN (Bulog) untuk menyerap gabah petani.
Lalu di mana titik masalahnya?
Jika dirunut, garis dasar subsidi pupuk kita adalah Urea dan NPK serta porsi kecil pupuk organik. Pemerintah juga menetapkan penerima subsidi adalah sembilan komoditas, di lahan kecil (di bawah 1 hektar). Berdasarkan kebutuhan permintaan petani, yang masuk kriteria penerima subsidi ada sekitar 16 juta ton. Kebijakan alokasi anggaran 2023 adalah sekitar 9 juta ton yang di antaranya 3,4 ton berupa NPK. Sehingga uang subsidi dialokasikan 6,95 juta ton ke urea dan masing-masing 1,376 ton impor unsur pospat dan kalium. Dengan demikian, dari sisi permintaan, kuantum penerima subsidi dipotong sekitar 7,5 juta ton.
Itu berarti jika petani mengeluh pupuk langka, dapat disebabkan mereka mendapatkan jatah yang kurang dari permintaannya; atau bisa juga tidak mendapatkan sama sekali. Sementara harga pupuk non subsidi cenderung mahal. Dengan kata lain, ada problem terkait alokasi subsidi dan selisih harga yang tinggi dari pupuk komersil (non subsidi).
Reformasi struktural
Mencermati hal-hal tersebut kiranya diperlukan reformasi struktural yang paling tidak meliputi beberapa hal yang harus mendapat perhatian.
Pertama, perlu penajaman tugas dan fungsi BI dalam ranah moneter dan uang stimulus yang merupakan ranah Kemenkeu. Tentu kita berharap kebijakan biaya pengelolaan moneter BI (burden sharing) dan alokasi stimulus pemerintah dapat tepat sasaran. Jangan sampai dukungan BI dan pemerintah cenderung hanya dirasakan kelompok piramida teratas ekonomi yang miskin empati. Barangkali salah satu alternatifnya adalah melalui operasi moneter khusus untuk menyerap off-taker (pengambilan) gabah petani di atas kemampuan Bulog. Likuditias instrumen tertentu seperti Sukuk Negara (SBSN) dapat dipertimbangkan sebagai swap dalam operasi burden sharing. Ini bertujuan agar impor dapat dikurangi dan biaya off-taker dianggap sebagai beban inflasi.
Kedua, perlu reformasi di sektor pupuk dan lahan pertanian. Jika berkaca pada pengalaman beberapa negara lain, tampaknya kita memerlukan audit dan pemetaan unsur hara tanah secara komprehensif. Pada titik tertentu, pola subsidi pemerintah mengarah ke pemupukan sesuai hasil audit per lahan tanah. Setidaknya inilah yang dapat dilakukan pemerintah di saat perang energi (gas) global yang turut mengerek kelangkaan pasokan gas amoniak—yang merupakan bahan baku Urea. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan lahan pertanian produktif dari berbagai gangguan (hama maupun keserakahan industri berdampak tidak ramah lingkungan).
Ketiga, transformasi teknologi di bidang pangan juga harus benar-benar matang dalam aspek kerangka perencanaan hingga eksekusinya.
Keempat, pemerintah perlu menetapkan kebutuhan domestik gas alam khusus yang dapat diterima industri pupuk dalam izin kuota ekspor. Di samping itu, eksportir amoniak dapat saja dikenakan wind fall tax sebagai off taker gabah petani.
Saya jadi teringat pesan Nabi Muhammad Saw: “Hal tunsharun wa turzaqun illa bi dhu’afaaikum” yang artinya kurang lebih: “Bukankah kalian dapat kemenangan dan rezeki atas jasa masyarakat kecil?”. Dalam penjelasan lain, hadis ini berisi wasiat: jika negara menginginkan kemenangan dan rizki yang berkelanjutan, harusnya pemegang kebijakan berpihak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berterima kasih kepada masyarakat kecil, termasuk petani kecil (gurem), melalui dukungan kebijakan. Bukan malah memandang subsidi kepada mereka hanya sekadar beban.
Allahu wa Rasuluhu A’lam.